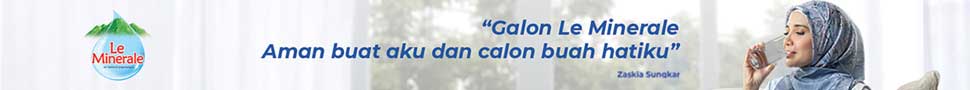Judicial Activism, Batas-Batas dan Upaya Mahkamah Agung Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum

Jakarta | HSB – Judicial activism adalah paradigma peradilan yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan diskresi judicial dalam penerapan hukum.
Judicial activism adalah paradigma peradilan yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan diskresi judicial dalam penerapan hukum.
Praktiknya, hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai aktor yang secara aktif menggali, menemukan dan menafsirkan hukum dengan tujuan agar putusan yang dijatuhkan menghasilkan keadilan substantif.
Judicial activism merupakan antitesis dari judicial restraint (pembatasan yudisial), yang berarti hakim harus tunduk dan terikat pada teks dalam undang-undang dan tidak boleh memperluas pada saat menerapkan hukumnya.
Sehingga, dapat dipahami bahwa judicial activism merupakan bentuk kreativitas hakim dalam mengisi kekosongan hukum dengan cara menggali, menemukan dan menafsirkan norma hukum secara progresif, menyeragamkan dan menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat yang berkembang.
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, di sisi lain Pasal 5 ayat (1) UU KKH menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
Pasal-pasal tersebut mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) secara kreatif demi memastikan keadilan tetap ditegakkan meskipun norma positif belum mengaturnya secara eksplisit.
Dari perspektif akademik, judicial activism berarti pandangan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, tetapi sistem yang hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam paradigma ini, hakim dianggap memiliki peran kreatif yang diberikan kewenangan untuk mengonstruksi hukum ketika norma-norma hukum tidak memberikan respons yang jelas dan akurat terhadap penyelesaian perkara konkret.
Judicial activism dilakukan ketika legislator tidak segera menanggapi perubahan dalam kehidupan sosial atau dalam situasi di mana norma-norma hukum yang ada tidak relevan lagi atau efektif dengan kebutuhan masyarakat.
Hakim dalam posisi ini, bukan hanya penafsir pasif dari undang-undang, tetapi juga penemu hukum yang secara konstruktif menafsirkan norma agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi, moralitas publik, dan prinsip hak asasi manusia.
Dalam praktik ketatanegaraan modern, judicial activism terlihat dalam putusan-putusan yang bersifat progresif seperti penemuan hukum baru dalam kekosongan peraturan hukum.
Di Indonesia, fenomena ini tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menegaskan keberpihakan pada keadilan substantif meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, salah satu contohnya adalah putusan Nomor 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996.
Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan jika pelaku (dader) perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima (Hasanah, 2017).
Praktik judicial activism berpotensi menimbulkan penyimpangan serta mengganggu konsistensi penerapan hukum apabila hakim bertindak melampaui batas kewenangan yudisialnya.
Oleh karenanya, diperlukan batasan-batasan yang tegas, jelas dan prinsipil agar tidak menyalahi fungsi kekuasaan kehakiman yang sesungguhnya.
Batasan-batasan tersebut antara lain:
1. Batas Legalitas dan Undang-Undang Organik
Secara yuridis parameter judicial activism sangat luas, oleh karena belum ada ketentuan yang memberikan batas-batas tertentu terhadap kreativitas judicial. Namun sejatinya, judicial activism tidak boleh bergeser menjadi judicial legislasi.
Artinya, hakim tidak boleh membuat norma hukum baru yang mengikat umum. Artinya secara etis tidak dibenarkan pembuatan undang-undang melalui jalur yudikatif melalui mekanisme judicial activism.
2. Batas Doktrin Judicial Restrain
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim diperbolehkan melakukan interpretasi ekstensif (perluasan) atau penemuan hukum secara progresif, sepanjang hal tersebut tetap berakar pada norma hukum yang ada, asas-asas hukum, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Batas Etis, Moral dan Profesionalitas
Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) U Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan hakim untuk mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang di dalamnya terkandung prinsip integritas, independensi, dan profesionalitas.
Batas etis ini, merupakan batas pengendali diri bagi hakim dalam melaksanakan praktik-praktik judicial.
Hakim wajib mengedepankan keadilan dan kemanfaatan secara obektif tanpa adanya intervensi dari luar, namun juga tidak menggunakan kekuasaan kehakiman untuk kepentingan pribadi, politik, atau ideologi.
Sehingga, praktik-praktik judicial activism dilakukan dengan tetap berpegang pada landasan argumentasi hukum yang kuat, transparan, dan rasional.
3. Batas Akademis dan Rasionalitas Argumentatif
Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam batas-batas sebelumnya, hakim dilarang untuk melegitimasi penerapan judicial activism di luar rasionalitas argumentatif yang semata-mata dibuat dan didefinisikan atas subyektifitas.
Hal ini berarti, penjatuh hukumannya tidak boleh didasarkan pada pertimbangan moral atau perasaan subjektif tentang keadilan, tetapi seharusnya memiliki legitimasi metodologis.
Sejalan dengan batas-batas tersebut, Djaniko M.H. Girsang (2025) berpendapat, “batas penafsiran hakim mencakup Prinsip legalitas, Asas-asas Hukum, Metode Penafsiran, Yurisprudensi dan Kode Etik Hakim”.
Sedangkan Syamsul Arief (2025) berpendapat, kebebasan Hakim tidak mutlak tanpa batas karena dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan, seorang Hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim (KEPPH).
Sepanjang mengenai penerapan hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan putusan, kebebasan hakim tidak mutlak tapi bersifat relatif, hanya terbatas dalam kerangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.
Hanya dalam batas ini, kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam melaksanakan penerapan hukum. Tujuan pemberian kebebasan yang terbatas dan relatif agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat indonesia (Harahap, 2017, hal. 54).
Di sisi lain, hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan harus menyesuaikan diri dengan semangat judicial restraint, acuan pokoknya adalah: limited in function dan judicial abstention.
Pertama, fungsinya terbatas yakni dalam memutus perkara penyelesaian perkara harus diputus semata-mata berdasarkan fakta-fakta sesempit mungkin.
Kedua, judicial abstention yang berpatokan pada kebolehan dan kebebasan hakim melakukan konstruksi hukum yang sangat terbatas (Abdullah, 2021, hal. 3).
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi yudisial bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya (absolut), melainkan kebebasan yang bersifat relatif dan dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang fundamental.
Jika diuraikan batas-batasan tersebut adalah prinsip legalitas, doktrinal, etis, moral dan rasional, asas-asas hukum, metode penafsiran, yurisprudensi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).
Dengan demikian, kebebasan hakim harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila, agar setiap putusan hakim tidak hanya memenuhi rasa keadilan individu, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial bangsa Indonesia.
Artinya, aktivitas yudisial yang dilakukan oleh hakim tidak boleh menyalahi hukum dan harus tetap menyesuaikan dengan norma hukum positif dan asas konstitusional yang berlaku.
Aktivitas tersebut tidak boleh menyebabkan fragmentasi di antara praktik peradilan, melainkan harus memperkuat kesatuan penerapan hukum di setiap tingkat peradilan.
Maka dari itu, diperlukan upaya Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan penerapan hukum sebagai konsekuensi dari praktik judicial activism di tengah tantangan keragaman budaya yang dapat diwujudkan melalui beberapa langkah antara lain:
1. Penetapan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Tambahan
Bertujuan agar lahir putusan-putusan yang seragam, dalam hal ini mahkamah Agung dapat menetapkan yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh hakim dalam memutus perkara konkret ketika terjadi kekosongan hukum. Setelah yurisprudensi ditetapkan, hakim di seluruh Indonesia dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan yurisprudensi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
Penetapan yurisprudensi, memungkinkan dilakukannya pengayaan terhadap hukum tanpa harus menunggu perubahan aturan positif dalam undang-undang.
Dengan begitu, diharapkan dapat meminimalisir disparitas putusan dan tercipta kesatuan dalam penerapan hukum.
2. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
SEMA sebagai pedoman internal, berfungsi memberikan pedoman teknis bagi para hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara. Melalui kebijakan-kebijakan dalam SEMA, Mahkamah Agung dapat meneguhkan arah penerapan hukum secara seragam, sekaligus mempertegas batas-batas judicial activism agar tidak menimbulkan disparitas putusan antar peradilan, misalnya dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang memberikan parameter pemidanaan dalam penerapan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Peningkatan Kapasitas Intelektual dan Integritas Hakim.
Kesatuan penerapan hukum tidak akan tercapai tanpa kesamaan paradigma berpikir antar hakim. Oleh karenanya, Mahkamah Agung harus mengembangkan program pendidikan berkelanjutan, misalnya continuing judicial education (CJE) yang menanamkan pemahaman tentang teori hukum progresif, hermeneutika hukum, serta batas-batas konstitusional dalam praktik judicial activism. Dengan demikian aktivitas yudisial dapat dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan berorientasi pada keadilan.
4. Optimalisasi Eksaminasi Putusan
Melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung telah meluncurkan inovasi e-Eksaminasi putusan (eksaminasi elektronik), hal ini diperlukan, agar dapat dilakukan eksaminasi secara aktif terhadap putusan-putusan hakim untuk mengidentifikasi potensi inkonsistensi penerapan hukum.
Mekanisme ini, tidak hanya memastikan kesatuan penerapan hukum, tetapi juga menjadi sarana refleksi sejauh mana judicial activism diimplementasikan oleh hakim secara proporsional dan sesuai koridor hukum.
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa judicial activism adalah ekspresi kreatif dan progresif hakim dalam menerapkan keadilan substantif di tengah-tengah keterbatasan norma hukum positif.
Akan tetapi, kebebasan hakim harus tetap berada dalam koridor prinsip legalitas, asas hukum, dan nilai-nilai konstitusional agar tidak bergeser menjadi bentuk penyimpangan wewenang.
Mahkamah Agung memiliki peran sentral dan tanggung jawab untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dengan berbagai instrumen kelembagaan dan kebijakan normatif.
Penetapan yurisprudensi, penerbitan SEMA, peningkatan kapasitas intelektual dan integritas hakim, dan optimalisasi mekanisme eksaminasi putusan, adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesatuan penerapan hukum di berbagai lingkungan peradilan.
Dengan demikian, praktik judicial activism dapat diarahkan secara proporsional untuk mengisi kekosongan hukum dan memperkuat sistem peradilan yang responsif, berkeadilan, dan berasas Pancasila.
Referensi
Abdullah, S. (2021). Juducial Activism. Sleman: Deepublish .
Arief, S. (2025, September 18). Dekonstruksi Putusan Hakim, Perjuangan Hakim Anak Keluar Dari Labirin Positivisme Hukum. kelas Inspirasi pada Diklat Seritifkasi Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum Seluruh Indonesia tahun 2025, Bogor, Jawa barat, Indonesia.
Girsang, D. M. (2025, Juli 30). Pembinaan Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura, Serui, Kab. Kepulauan Yapen, Papua, Indonesia.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hasanah, S. (2017, April 28). Hukumonline.com. Retrieved Oktober 23, 2025, from Hukumonline.com Sudah Dipidana Secara Adat, Dapatkah Dipidana Lagi Berdasarkan Hukum Nasional?: https://www.hukumonline.com/klinik/a/sudah-dipidana-secara-adat–dapatkah-dipidana-lagi-berdasarkan-hukum-nasional-lt57dd96e1ea96c/
Penulis: Ardiansyah Iksaniyah Putra